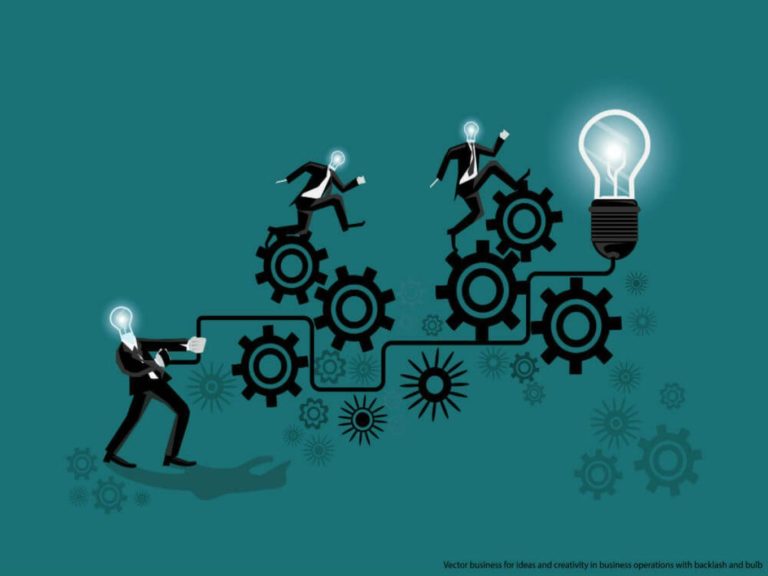Deep Learning: Back To…

Deep Learning: Back To School Home
Sebagaimana siklus pergantian kepemimpinan nasional setiap 5 tahun, demikian juga yang terjadi dengan kurikulum pendidikan di Indonesia. Kali ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah membawa pendekatan baru yang disebut dengan deep learning. Pendekatan deep learning dapat diartikan sebagai pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman mendalam, penguasaan kompetensi, dan keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar, bukan sekadar penguasaan materi secara superficial. Kebalikan dari deep learning adalah surface learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang lebih fokus pada penghafalan dan pemahaman dangkal terhadap materi. Jika dianalogikan sebuah bangunan, surface learning adalah bagian di atas permukaan tanah dari bangunan tersebut, sedangkan deep learning adalah fondasinya.
Fondasi adalah dasar dari sebuah bangunan. Meskipun tidak tampak, fondasi ini sangat menentukan kekokohan dan keberlangsungan bangunan tersebut. Misalnya, seberapa lama usia bangunan tersebut, seberapa tahan bangunan tersebut terhadap gangguan eksternal, dan seberapa tinggi bangunan tersebut dapat dibangun. Oleh karena itu, seluruh pihak yang terlibat dalam proses konstruksi sebuah bangunan pasti sepakat bahwa fondasi ini adalah hal yang paling awal harus disiapkan dan mereka rela mengalokasikan biaya dan waktu yang relatif besar/banyak untuk memastikan fondasi terbangun dengan baik. Demikian pula dengan anak, deep learning merupakan fondasi yang menentukan seberapa kuat dia mampu belajar dan berjuang menghadapi tantangan di masa yang akan datang.
Hasil dari deep learning ini adalah terbentuknya growth mindset (pola pikir bertumbuh) yang baik pada anak. Growth mindset artinya keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan seseorang dapat dikembangkan melalui usaha, pembelajaran, dan ketekunan. Kebalikan dari growth mindset adalah fixed mindset (pola pikir tetap), yaitu keyakinan bahwa kemampuan dasar seperti kecerdasan, bakat, dan karakter adalah sesuatu yang sudah tetap dan tidak dapat diubah.
Anak yang memiliki growth mindset yang baik tidak akan menghindari tantangan, tetapi justru berani menghadapinya. Dia yakin bahwa ada banyak solusi yang dapat dicari, dikaji, dan dilaksanakan untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Ketika mendapat masalah dalam menyelesaikan tantangan tersebut, dia tidak akan menyerah, tetapi akan bertahan untuk menyelesaikannya. Dia yakin bahwa jika masih gagal, bukan karena dia tidak bisa, tetapi karena saat ini belum bisa, dan dia pun insyaAllah akan bisa menyelesaikannya suatu saat nanti jika terus belajar dan berusaha.
Seseoran dengan growth mindset, kalaupun ternyata dia tetap pada akhirnya gagal dalam menyelesaikan masalah, dia tidak akan merasa upayanya sia-sia. Apapun hasilnya, pasti ada hikmah yang dapat dipetik dalam perjuangannya tersebut. Meskipun dalam perjuangan dan hasil yang diperolehnya menerima kritikan, dia tidak akan baper, tetapi justru menjadikannya bahan bakar perbaikan dirinya. Bahkan jika dia tidak berhasil namun rekannya berhasil, dia tidak akan merasa iri, tetapi justru terinspirasi untuk belajar lebih jauh dari rekannya tersebut agar bisa turut berhasil juga. Dengan seluruh karakteristik growth mindset seperti ini, kita semua semestinya sepakat bahwa karakter tersebut sangat dibutuhkan oleh anak di zaman yang sangat menantang dan penuh ketidakpastian seperti saat ini maupun di masa depan.
Generasi muda saat ini mengalami begitu banyak tantangan yang sangat dinamis. Terbukti dalam 5 tahun terakhir, terdapat begitu banyak perubahan signifikan di seluruh aspek kehidupan. Di bidang politik, terdapat banyak pergantian kepemimpinan nasional di seluruh dunia yang menimbulkan ketidakstabilan politik dan keamanan dunia, seperti perang dagang Amerika Serikat-Cina maupun perang fisik seperti Rusia-Ukraina. Di bidang sosial budaya, pandemi mengubah perilaku masyarakat secara signifikan terutama terkait adopsi digital. Hampir seluruh aktivitas saat ini sangat tergantung dengan teknologi digital, baik yang bersifat membangun maupun yang bersifat merusak. Di bidang ekonomi, resesi global berpengaruh juga terhadap kondisi ekonomi dalam negeri yang tercermin dalam penurunan daya beli dan banyaknya pemutusan tenaga kerja sehingga bonus demografi Indonesia terancam berubah menjadi beban demografi karena banyaknya tenaga kerja yang kesulitan memperoleh pekerjaan.
Tantangan dan ancaman terhadap generasi muda Indonesia tentunya tidak hanya berhenti di sini, tetapi akan terus terjadi di masa yang akan datang. Hal ini membutuhkan mindset (pola pikir), pengetahuan, keterampilan, maupun karakter yang unggul sebagaimana dicita-citakan oleh Mendikdasmen dengan pendekatan deep learning-nya. Namun, kami memandang bahwa pendidikan bersifat holistik sehingga harus dikelola menggunakan pendekatan yang holistik juga.
Mindset merupakan pola pikir seseorang yang mempengaruhi seseorang dalam memandang dan merespons sesuatu sehingga mindset sangat memengaruhi perilaku seseorang sehari-hari. Sebaliknya, perilaku seseorang sehari-hari sangat mencerminkan mindset orang tersebut. Orang tua yang tidak memiliki growth mindset tentunya akan tecermin dari bagaimana perilaku mereka sehari-hari maupun terhadap anak mereka. Sebagai contoh, orang tua yang tidak memiliki growth mindset akan merespons negatif terhadap anak yang banyak bertanya atau ingin tahu kepada orang tuanya. Respons negatif tersebut akan membentuk mindset anak bahwa rasa ingin tahu memberikan dampak negatif untuk dia, sehingga di masa depan dia cenderung lebih memilih memendam rasa ingin tahu karena khawatir terhadap dampak negatif yang akan diterimanya.
Sebagaimana fondasi sebuah bangunan, mindset terbentuk di fase awal anak belajar, dan itu bukan di sekolah, melainkan di rumahnya masing-masing. Pendidiknya juga bukan guru, melainkan orang tuanya masing-masing. Selain itu, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pembentukan mindset sangat dipengaruhi oleh perilaku orang-orang yang banyak berinteraksi dengan anak tersebut. Semakin seseorang banyak interaksi dengan anak tersebut, semakin besar pula pengaruh orang itu terhadap pembentukan mindset sang anak. Orang yang paling banyak berinteraksi dengan anak sejak kecil tentunya bukan gurunya, melainkan orang tuanya, sehingga kami memandang peran orang tua dalam mendidik anak di rumah merupakan faktor kunci keberhasilan pendekatan deep learning ini.
Dalam setiap pergantian kurikulum, fokus aktivasi maupun sosialisasinya lebih banyak penekanan pada guru dan murid, sementara orang tua jarang dijadikan tokoh kunci dalam pendidikan tersebut. Akibatnya, makin hari orang tua banyak yang makin tidak sadar peran pentingnya dalam pendidikan anak dan bahkan terkadang menyerahkan sepenuhnya pada sekolah. Dalam pendekatan deep learning ini, tanpa peran aktif orang tua, kecil sekali kemungkinan sekolah dapat berhasil membentuk growth mindset anak. Sebagai contoh, dalam growth mindset yang menjadi fokus adalah proses, bukan hasilnya. Ketika anak banyak bertanya dan aktif berdiskusi di kelas namun nilainya belum maksimal, sudah semestinya dengan pendekatan deep learning guru memberikan apresiasi atas keaktifan dan keingintahuan anak tersebut di kelas. Namun, jika orang tuanya belum memiliki growth mindset, ketika sampai di rumah anak akan ditanya nilainya bahkan bisa jadi dimarahi karena nilainya yang masih kurang maksimal meskipun sudah menunjukkan perilaku growth mindset yang baik di kelas. Akibatnya, anak akan cenderung pragmatis fokus ke nilai, bahkan terkadang dengan cara apapun, dibanding berproses dan mengembangkan growth mindset-nya.
Rekomendasi kami adalah mendorong upaya yang lebih holistik, sistematis, dan terintegrasi, disertai dengan upaya yang sangat serius dalam melibatkan orang tua sebagai peran kunci dalam pendekatan deep learning ini. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa meskipun sesuai amanat undang-undang dasar bahwa minimal 20% Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) wajib dialokasikan untuk fungsi pendidikan, pada praktiknya pos angggaran ini tidak seluruhnya digunakan untuk pendidikan. Sebagai contoh, dana desa maupun dana sosial termasuk yang mendapatkan alokasi dana fungsi pendidikan ini. Tanpa perencanaan dan pengendalian yang kuat, penggunaan anggarannya berpotensi tidak selaras atau tidak koheren dengan konsep pendidikan yang dirancang.
Kemendikdasmen seyogianya diberi kewenangan untuk mengoordinasi dan memastikan keselarasan program dan pengendalian penggunaan dana pendidikan di seluruh kementerian atau lembaga yang menerima alokasi dana pendidikan APBN. Dengan kewenangan tersebut, pendekatan holistik, sistematis, dan terintegrasi dapat dilakukan. Dana desa maupun dana sosial semestinya dapat digunakan untuk mendidik dan memberi insentif para orang tua maupun lingkungan masyarakat agar memahami dan turut berperan aktif dalam pendidikan menggunakan pendekatan deep learning ini di rumah masing-masing dan lingkungan sekitarnya. Tanpa pendekatan yang sistematis dan terintegrasi untuk menghilangkan ego sektoral dan memastikan keselarasan gerakan pemerintah dalam pendidikan anak secara holistik, tidak hanya di sekolah maupun juga di lingkungan rumah, sepertinya cita-cita mulia pendekatan deep learning ini akan sangat sulit terwujud, bahkan berpotensi mengacaukan pendidikan anak karena perbedaan pendekatan maupun mindset guru sebagai pendidik di sekolah dengan orang tua sebagai pendidik di rumah. Belum lagi ditambah dengan potensi berubahnya lagi kurikulum atau pendekatan ketika terjadi pergantian kepemimpinan nasional di 5 tahun berikutnya.
S1 Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada (2003-2007), S2 Teknik Elektro King Saud University (2007-2010), memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap pengelolaan sumberdaya manusia dan pendidikan, Saat ini menjadi karyawan bidang Strategic Management di Telkom Indonesia dan Advisory Board Teknik Elektro Universitas Islam Indonesia.