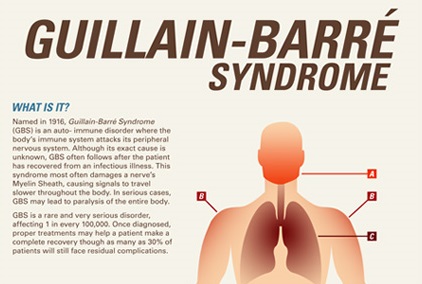Perkenalan dengan Stres

Secara bahasa, stres tampaknya sudah menjadi sebuah istilah yang cukup populer digunakan. Kata ini mudah terucap oleh orang-orang dalam berbagai keadaannya masing-masing. Menghadapi jalanan yang macet, stres. Menghadapi dosen yang galak, stres. Menghadapi ujian, juga stres. Tapi, sebenarnya apa itu stres?
Dari fisika ke psikologi
Terminologi stres sebenarnya terlebih dahulu digunakan dalam bidang fisika, yaitu “stress”, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi “tekanan”. Tekanan sendiri secara sederhana dapat dipahami sebagai gaya dari luar benda yang dalam batas tertentu dapat mengubah keadaan benda tersebut.
Berawal dari kajian di bidang fisika, stres kemudian mulai dikaji dalam konteks psikologi. Di dunia psikologi, ahli yang dianggap sebagai pionir dalam riset-riset mengenai stres adalah Hans Selye pada tahun 1950-an. Pada eksperimen yang awalnya bertujuan menemukan hormon baru ini, Seyle justru mendapatkan ilham mengenai konsep stres pada organisme. Meminjam istilah yang sudah populer di bidang fisika, Selye kemudian menggunakan istilah stres untuk menyebut efek dari stimulus luar (berupa substance yang merusak) yang dia ujikan pada organisme (tikus).
Definisi stres yang sepertinya cukup merangkum pendapat para ahli adalah definisi dari Santrock (2005). Stres didefinisikan sebagai respon seseorang, baik fisik maupun psikologis, terhadap stresor, yaitu segala keadaan ataupun peristiwa yang mengancam dan menguji kemampuan bertahan seseorang.
Respon fisiologis seseorang terjadi melalui mekanisme biologis dalam tubuh yaitu dengan mengeluaran senyawa kimia tertentu yang berasal dari bagian otak untuk memicu perubahan tertentu pada sistem tubuh, seperti naiknya tekanan darah, jantung yang berdegup lebih kencang (deg-degan), keringatan, sakit perut, sakit kepala dan sebagainya. Selain respon fisiologis, biasanya juga dibarengi dengan respon psikologis yang muncul antara lain cemas, gelisah, galau, dan sejenisnya.
Stres baik vs stres buruk
Dalam dunia psikologi, stres adalah terminologi yang mempunyai makna “netral”. Namun, penggunaan dalam bahasa dan budaya Indonesia menunjukkan bahwa istilah stres cenderung dipersepsi negatif. Dengan kata lain, stres adalah kata yang mempunyai makna yang negatif, jelek, buruk. Padahal, sebenarnya tidak demikian.
Salah satu konsep yang cukup berkembang dalam kajian mengenai stres ini adalah penilaian kognitif (cognitive appraisal) terhadap stres dari Richard S. Lazarus (Durand & Barlow, 2006). Penilaian kognitif atas stresor yang datang menjadi semacam “hakim” yang memutuskan apakah stresor itu akan dianggap sebagai stres atau bukan.
Menurut penelitian-penelitian terkait, stresor baru akan dianggap sebagai stres yang menuntut seseorang untuk beradaptasi ketika sudah melewati satu lapis pertahanan mental manusia yang disebut sebagai penilaian kognitif tadi. Ketika stresor datang, manusia akan terlebih dahulu mengaktifkan penilaian kognitif untuk memutuskan apakah stresor itu dianggap mengancam atau tidak.
Jika dianggap mengancam, proses selanjutnya adalah mengaktifkan lapis pertahanan mental yang kedua, yaitu penilaian kognitif lanjutan mengenai kemampuan diri dalam menghadapi stresor tersebut. Jika dirinya menilai mampu, akan terjadi apa yang disebut sebagai stres baik (eustress). Sebaliknya, jika tidak mampu, akan terjadi stres buruk (distress).
Stres baik adalah stres yang membuat seseorang yang mengalaminya melakukan tindakan-tindakan positif (diterima secara budaya dan moral) yang memungkinkan untuk mengatasi stresornya tersebut. Sebaliknya, stres buruk merupakan stres yang membuat seseorang melakukan tindakan negatif untuk mengatasinya.
Jika pada lapis pertama penilaian kognitif tadi justru menyimpulkan bahwa stresor yang datang itu tidak mengancam, selesailah perkara. Ini berarti bahwa seseorang itu tidak sedang menghadapi stres sehingga tidak memerlukan respon adaptif untuk mengatasinya.
Sebagai contoh, siswa yang akan menghadapi Ujian Nasional (UN) cenderung mempersepsi UN tersebut sebagai stresor. Selanjutnya, dia akan menilai apakah momen UN yang dihadapinya itu mengancam atau tidak. Jika tidak, berarti tidak terjadi stres. UN akan dihadapinya dengan perasaan “biasa saja”, tanpa perlu kehebohan yang lazim terjadi di antara para siswa.
Jika ternyata dianggap mengancam, dia kemudian menilai apakah mampu untuk menghadapinya. Jika mampu, akan terjadi stres baik yang diwujudkan dalam bentuk, misalnya, belajar lebih giat, belajar bersama kawan, latihan soal lebih banyak, serta berdoa dan beribadah lebih rajin. Jika tidak mampu, bisa saja berakhir dengan bunuh diri, narkoba, atau tindakan pelarian lain yang tidak pantas secara budaya dan moral.
Anda yang menentukan
Jika menganut teori Lazarus yang cukup populer tadi, stres atau tidak itu kembali kepada masing-masing individu, bagaimana menyimpulkan stresor yang datang. Kesimpulan itu pun dapat dibangun melalui serangkaian “latihan-latihan” dalam menghadapi berbagai momen dalam kehidupan. Semakin banyak berlatih, tentu semakin mahir. Itulah mengapa dalam menghadapi momen yang kurang lebih sama, orang tua akan cenderung mengatasinya dengan lebih baik ketimbang mereka yang lebih muda.
Referensi:
Santrock, J. W. (2005). Introduction to Psychology, 2nd Edition. New York: McGraw-Hill.
Durand, V. M. & Barlow, D. H. (2006). Intisari Psikologi Abnormal Edisi Keempat. (H. P. Soetjipto & S. M. Soetjipto, Penerj.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Penulis:
Ridwan Aji Budi Prasetyo, menyelesaikan S1 di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sempat bekerja sebagai staf SDM pada sebuah BUMN jasa konstruksi sebelum memutuskan menjadi asisten di Laboratorium Rekayasa Sistem Kerja dan Ergonomi ITB, Bandung. Akan melanjutkan memulai studi S2 pada Bulan September 2014, biidznillah, di Program Studi Human Factors and Ergonomics, University of Nottingham, Inggris, dengan mengambil kekhususan pada kajian human error in transportation.